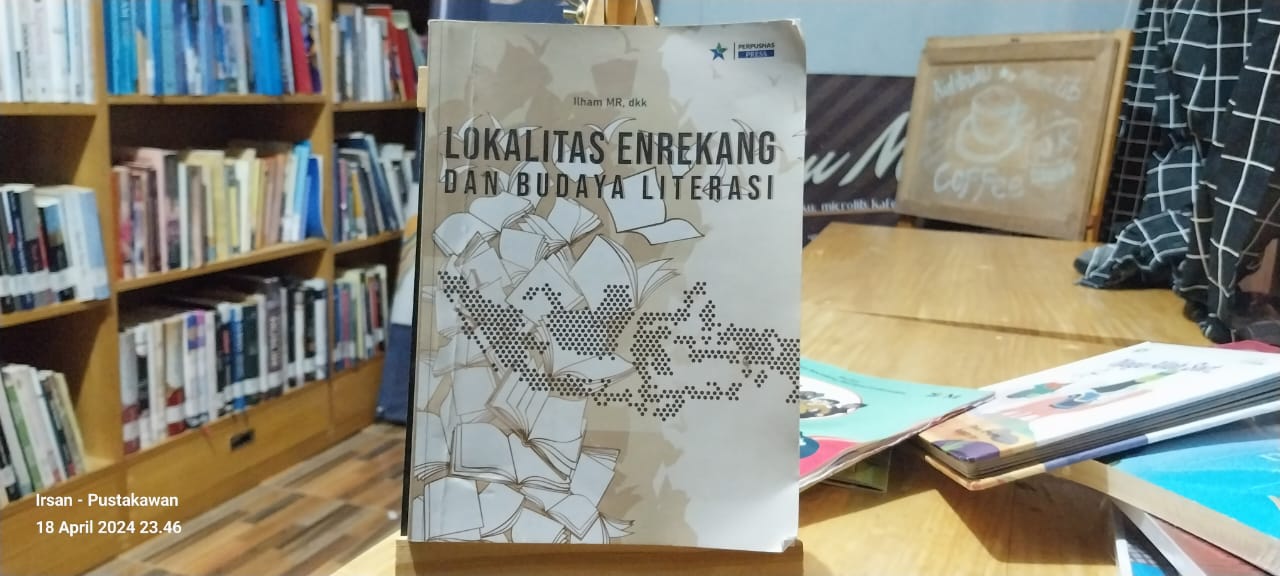Sejak ia memutuskan untuk mengelola lahan perkebunan ayahnya, tak ada kesibukan lain, selain mengurus kebun, yang ia lakukan kecuali bercerita bersama anak-anak di desa tersebut. Mulanya, ia merasa resah karena anak-anak di desanya sering mengejeknya lantaran kuliah jauh-jauh di Jerman namun setelah sarjana malah jadi petani cokelat yang bahkan hasil panennya tidak mampu menggantikan biaya kuliahnya di Jerman selama empat tahun.
Banyak orang yang telah menawari Bagong pekerjaan. Bahkan ada pula yang ingin mencalonkannya jadi Bupati karena hanya ia yang pernah kuliah di Jerman. Namun ia memilih menjadi petani cokelat. Ayahnya pun terperanjat ketika mengetahui anaknya memilih bertani. “Seandainya kau bilang dari dulu, ayah tak perlu repot menjual tanah untuk biaya kuliahmu.”
Sama seperti biasanya, selepas berkebun, Bagong menunggu di pinggir lapangan tempat anak-anak itu sering bermain sepak bola, lalu bercerita dengan mereka. Maka ia memanggil satu persatu anak-anak itu lalu diajaknya bercerita. Cerita dimulai dan anak-anak yang kecapaian bermain bola dengan khidmat mendengarkan.
“Membosankan,” keluh Anwar, anak Kepala Desa, yang paling antusias mendengarkan cerita Bagong sedari awal.
Ketika Bagong bercerita untuk pertama kalinya dengan mereka, ia menceritakan kehidupannya di Jerman, bahwa di sana tak ada dangke yang selama ini anak-anak itu sering keluhkan lantaran dangke rasanya hambar. Juga di sana anak-anak seperti mereka tidak perlu bermain bola di lapangan yang bidangnya tidak rata dengan gawang bambu yang jika tersentuh bola pelan pun, tiang itu roboh. “Kalau begitu, aku juga mau ke Jerman,” ucap Anwar ketika itu, lalu teman-temannya mengikuti, “aku juga…aku juga.” Namun karena Bagong tak lagi bercerita tentang kehidupannya di Jerman, Anwar mulai bosan, begitu pun teman-temannya.
“Anak-anak,” Bagong mencoba menenangkan. “Ceritaku belum selesai.”
Sementara umpatan dari anak-anak itu makin keras, salah satu dari mereka berkata, “benar kata Anwar, kami tak mau lagi mendengar ceritamu. Membosankan!” Mereka lalu pulang menyisakan Bagong yang tak mengerti mengapa anak-anak seperti mereka enggan mendengarkan cerita tentang Enrekang, tempat kelahiran mereka sendiri.
Seminggu berlalu dengan umpatan-umpatan Anwar dan teman-temannya. Umpatan yang seharusnya tak lagi Bagong dengarkan, malah membuat Bagong semakin menderita. “Sarjana tidak berguna, sampah masyarakat!” Kata anak-anak itu suatu waktu sambil berlari karena Bagong memburu mereka dengan kayu jati.
Hari yang ditunggu Bagong tiba. Ia melihat Anwar menangis di pinggir lapangan. Ia mendekati Anwar yang sedang memeluk lututnya sambil menyembunyikan mukanya yang menangis di balik lutut itu. Ia menenangkan anak itu dari tangisnya, mencoba menemukan celah di balik kesedihan itu. Rencana ini telah dipikirkannya jauh hari, sejak ia mengecewakan pendengar setianya yang sudi duduk dengan berbagai aroma keringat untuk mendengarkan ceritanya.
Perlahan Anwar mulai bercerita. Ia dipukuli lantaran tak naik kelas. Sudah dua tahun ia duduk di kelas satu sekolah menengah. Katanya, ia mempermalukan nama besar ayahnya yang juga sudah dua tahun tak diganti sebagai Kepala Desa. “Bukankah itu juga prestasi. Ayah tak diganti selama dua tahun, aku pun tak tergantikan di kelas satu dengan tahun yang sama,” ucapnya sambil tersedu-sedu. Bagong bingung harus memberi saran macam apa. Namun, Anwar berjanji kepada Bagong bahwa ia akan memanggil lagi temannya untuk mendengarkan cerita Bagong sebagai hadiah karena Bagong telah sudi mendengar keluhannya.
Cerita Bagong dimulai kembali setelah Anwar mengingatkan temannya tentang pentingnya mengetahui asal-usul tanah kelahiran. Ia menyadari betapa dirinya sangat bodoh lantaran tak tahu apa-apa tentang Enrekang kecuali Poppo dan Parakang. Selepas bermain bola, mereka lagi-lagi mendengarkan cerita Bagong. Ia mulai bercerita perihal nama “Enrekang” bahwa Enrekang asal katanya Endek atau naik. Ia juga mengatakan bahwa, di Enrekang, dahulu ada kerajaan yang bernama Malepong Bulan. Tak lupa, Bagong menjelaskan kepada mereka mengapa bahasa Enrekang berbeda. “Mengapa kak?” Kata Anwar antusias. Bagong menjawab bahwa itu karena Enrekang berada di antara tiga suku, Toraja, Mandar, Bugis.
“Lalu apa untungnya semua itu, bukankah di Jerman lebih menyenangkan?” Kata teman Anwar.
Bagong sedih mendengar pertanyaan itu. Selama ia di Jerman, tak ada satu pun yang ia rindukan selain kampung halaman. Di Jerman, ia pernah melihat rumah yang dibongkar hanya karena rumah itu akan dipindahkan ke suatu tempat yang jaraknya tak sampai lima puluh meter dari rumah tersebut. Melihat itu, ia menyayangkan rumah kayu yang dibongkar itu, karena selama di Enrekang, ia pernah melihat ayahnya bersama pemuda desa mengangkat rumah yang bahkan akan dipindahkan sejauh dua ratus meter. Juga kehidupan malamnya. Sama seperti kebanyakan kota-kota di seluruh dunia, di sana jam dua belas malam masih banyak mobil yang lalu-lalang. Pernah ia memimpikan Enrekang menjadi kota seperti itu. Namun menurutnya, itu semua tak berguna. Terlebih masyarakatnya. Di sana terlalu bebas. Orang bisa melakukan apapun. Di Enrekang, anak yang berkeliaran jam sembilan akan dicari orang tuanya di tempat persembunyian yang paling sulit ditemukan sekalipun.
“Anak-anak,” ia menjelaskan. “Tak ada yang lebih nyaman dari pada di rumah sendiri, kalian mengerti maksudku bukan? Di Jerman, aku bahkan memuntahkan makananku setiap saat. Tak ada yang enak di sana. Lebih enak dangke.”
Ia melanjutkan dengan sedikit terisak. Mengetahui bahwa anak-anak di desanya tak suka dengan dangke membuatnya miris. Padahal, pernah suatu waktu ibunya mengiriminya dangke. Ia pun tak begitu mengerti mengapa dangke itu masih bisa utuh sampai ke Jerman. Lalu dangke itu diberikan kepada pemilik kontrakan tempat ia tinggal. “Ini lebih enak dari keju,” ucap pemilik kontrakan itu dengan bahasa Jerman. Berselang beberapa hari, permilik kontrakan itu, yang kebetulan juga adalah panitia penyelenggara festival kuliner yang beberapa hari kemudian akan diselenggarakan, mengatakan kepada Bagong membawa sebanyak mungkin dangke ke Jerman untuk diikutsertakan pada festival kuliner tersebut.
Melihat Bagong mengucurkan air mata, Anwar segera membuka bajunya yang penuh dengan keringat, lalu menyeka air mata Bagong dengan baju itu.
Seakan tak mau beranjak dari lapangan, Anwar terus memaksa Bagong bercerita. Bagong bercerita kembali. Kali ini ia bercerita tentang mitos Gunung Bambapuang, bahwa gunung itu dahulu menjulang tinggi. Saking tingginya, gunung tersebut runtuh, lalu penduduk yang bermukim di kaki gunung sontak berlari menghindari reruntuhan gunung tersebut. Konon, orang yang berlari akan menjadi batu ketika menoleh ke belakang melihat reruntuhan itu.
“Jadi, batu yang ada di sepanjang jalan menuju Anggeraja itu manusia?” Kata Anwar takjub.
“Tidak juga,” jawab Bagong.
“Aku pernah ke Baraka. Di pinggir jalan, aku melihat ada gambar orang di batu tidak jauh dari Gunung Bambapuang. Apa ia juga dikutuk?”
“Tidak Anwar, tidak. Itu baliho iklan.”
Cerpen ini diikutkan dalam Lomba Cerpen yang diadakan oleh Dispustaka Enrekang.