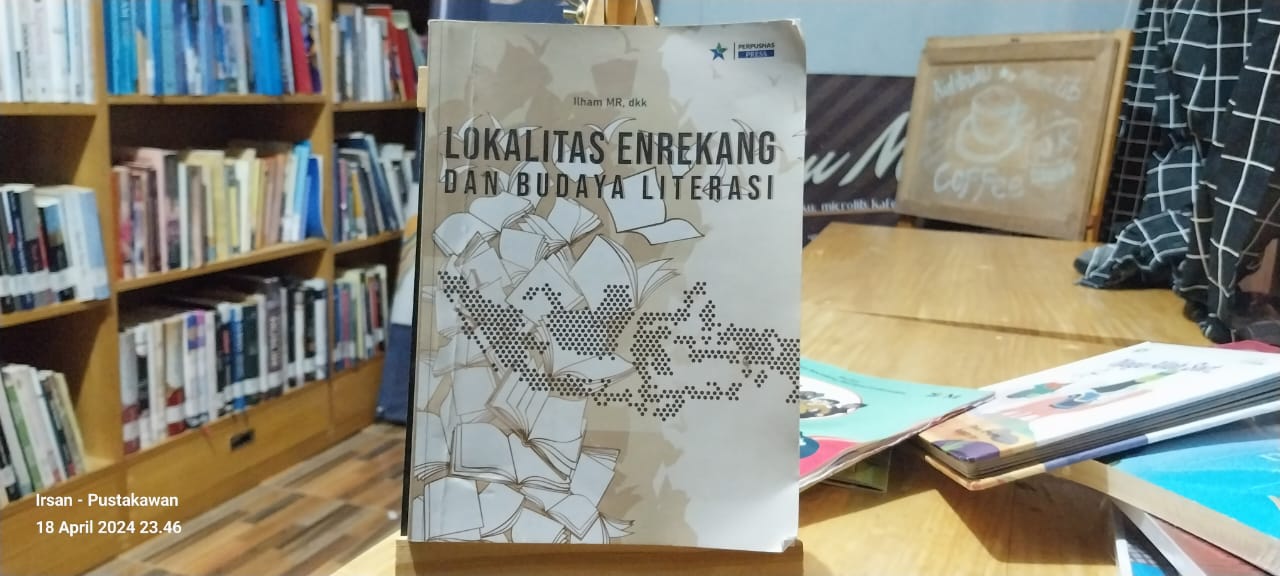Pagi itu, Nenek Ina duduk menghadap tungku, meniup-niup tumpukan bara api dengan corong peniup usang yang terbuat dari potongan bambu kering. Penat ia berjibaku dengan asap tebal yang mengepul, menyebar ke mukanya. Diusapnya air yang memenuhi kantung luar mata yang tampak keriput itu. Belum juga kayu yang ia tumpuk di perapian menyala. Kulit luarnya masih basah. Itupun dipungut di sela-sela rumput yang berembun lantaran hujan tak berhenti semalaman dan baru reda lepas subuh tadi.
Sementara di samping tungku, berdiri beberapa tiang kayu jati putih menyangga gubuk reyotnya. Bentuknya sudah tidak simetris lagi. Berlubang dan seringkali dilalui gerombolan rayap yang mengebor dan membuat sarang di sana. Tapi, Nenek Ina masih bersyukur, tiang itu masih setia memikul gubuk tuanya selama puluhan tahun. Dindingnya terbuat dari tatakan bambu, berlubang karena dimakan usia. Lapuk dan berdebu. Kelebihannya hanya menahan hembusan angin saat malam tiba. Selebihnya, tak ada apa-apa menggantung di sana. Tak ada foto keluarga. Tak ada cat yang menyamarkan warnanya sehingga tampak jelas bahwa itu adalah dinding dari bambu. Di sudut kiri hanya menempel sebuah kalender edisi Tahun 2014. Tak dikenalnya rupa orang yang ada di situ. Ia hanya ingat, kalender itu diberikan seorang lelaki berjaket kulit hitam dan bertopi, suruhan caleg yang tampak ramah berkoar-koar tentang program andalan juragannya kalau saja diberi kesempatan duduk di kursi empuk ruang dewan nanti. Tapi Nenek Ina tak peduli tentang program itu. Sama sekali tak tertarik.
Kini, setelah cukup hangat dilahap api, tumpukan kayu di dalam tungku perlahan mulai membara. Mengigit-gigit ranting kecil yang terselip diantara arang-arang yang mulai menyala.
Menyebarkan panas ke dasar wajan yang berisi tumpukan biji-biji kopi di atasnya. Serta-merta Nenek Ina mengambil sendok kayu yang tergeletak di samping tungku. Diaduknya biji-biji kopi itu dengan pelan, dengan irama yang lambat. Selambat nasibnya yang tak kunjung berubah. Semakin panas api, semakin cepat ia mengaduk-aduk biji kopi agar matangnya merata. Sebenarnya, lengannya itu sudah tidak cekatan seperti beberapa tahun lalu. Lemah dan seringkali nyeri jika harus mengaduk-aduk hingga berjam-jam lamanya. Tapi tetap saja dilakukannya lantaran ia tidak punya pilihan lagi. Tepatnya, tidak punya pekerjaan yang bisa sedikit meringankan beban hidupnya yang tinggal sendiri tanpa sanak saudara selain menyangrai biji kopi setiap hari selama musim kopi.
Tidak banyak hasil yang ia dapat setiap kali menyangrai kopi. Pohon kopi yang berbuah di sekitar gubuknya hanya sedikit saja. Itupun hanya beberapa bulan sekali. Berbuah pada musim yang tak tentu. Karung kecampang kecil yang ia gunakan saat memetik buah kopi tak pernah penuh.
Pekerjaannya hampir selesai. Sisa mendinginkan biji-biji kopi yang sudah menghitam tadi pada sebuah baki. Setelah dingin, pekerjaan lainnya sudah menanti. Menumbuk biji-biji itu hingga halus lalu disaring. Setelah itu dibungkus dengan plastik kecil transparan dan direkatkan ujung plastik pembungkus tadi dengan api dari lampu pelita.
Hari ini, kebetulan Pasar Sudu sedang ramai. Setiap hari Selasa dan Jumat Nenek Ina menjajakan kopi bubuk berbungkus plastik bening buatannya itu di lapak kecil di sudut pasar. Tidak jarang orang-orang yang lewat hanya meraba-raba bungkus kopinya itu tanpa membelinya. Nenek Ina paham, kopinya sudah banyak ditinggal pembeli. Zaman sekarang, orang-orang lebih senang nongkrong di kafe menyeruput kopi sembari berdiskusi dan berceloteh. Ia menghela napas panjang. Ia maklum dengan perubahan minat orang-orang. Buah bulat ajaib itu sering jadi buah bibir dimana-mana. Kopi kini telah jadi budaya. Tepatnya budaya gengsi. Kini kopi adalah minuman prestisius, khas orang-orang berduit. Langganannya kini hanya ibu-ibu rumah tangga yang tidak terlalu doyan dengan kafein, tapi kadang suami mereka ingin dibuatkan kopi hangat untuk dibawa ke kebun.
Lamunan Nenek Ina terhenti. Seorang pembeli, yang tampak asing dan baru kali ini dilihat, berhenti di depannya sambil melirik-lirik dagangan yang bertumpuk di lapak kayu tua itu.
“Dibuat sendiri, Nek?” tanya lelaki tadi.
Agak lama Nenek Ina menyahut. Diperhatikan sepintas lelaki paruh baya itu. Kelihatannya seperti seorang yang bekerja di kantor-kantor. Ia menduga lelaki itu mungkin seorang pegawai negeri, atau bahkan pengusaha. Pengusaha sukses tepatnya.
“Iya, Nak. Ditumbuk sendiri” balasnya.
Lelaki tadi pun berlalu. Dan Nenek Ina seperti biasa, tanpa ekspresi, kalem, lugu, hanya memandangi punggung calon pembelinya yang tidak berniat meneruskan transaksi. Pandangannya kembali ke tumpukan plastik berisi bubuk-bubuk kopi.
“Berapa satu bungkus, Nek?”
Nenek Ina kaget, tapi segera menguasai keadaan. Lelaki itu kembali dan kini, Nenek Ina punya keyakinan, layaknya keyakinan orang awam, firasat orang tua yang polos, lelaki itu bisa jadi pembeli pertamanya hari ini.
“Lima ribu, satu, Nak”`
“Berapa kasi’ ki’, Nak?” jawabnya sabar.
Sejenak lelaki itu berpikir. Kemudian bertanya lagi.
“Saya mau semuanya, Nek! Tolong bungkuskan.” Balas lelaki tadi menyederhanakan proses jual-beli.
Betapa senang hati Nenek Ina mendengar ucapan pembeli pertamanya itu. Namun, belum sempat ia mengambil kantong plastik untuk menaruh pesanan tadi, lelaki itu kemudian berkata lagi.
“Tapi, boleh kah saya bayar nanti, Nek.
Tidak bawa ka’ uang ini?”
Lelaki itu berusaha meminta persetujuan. Ia terlihat buru-buru tapi bubuk kopi itu terlalu menggodanya. Dengan aksi memborongnya, ia pikir itu adalah cara yang tepat untuk memonopoli bubuk hitam harum nan khas itu. Bubuk kopi yang jarang ada di masa sekarang lantaran masih diproduksi secara tradisional.
Dengan wajah lugu dan pandangan polos, Nenek Ina mengiyakan. Meski pembeli pertama itu baru dikenalnya, juga belum menjadi langganannya, tapi ia yakin, Allah Maha Adil. Ia sandarkan reski dan pengharapan pada-Nya. Disodorkannya kantong plastik besar berisi bungkus-bungkus kecil kopi bubuk dengan mantap seolah telah lama ia mengenal sosok lelaki yang berdiri dihadapannya. Sebelum meninggalkan lapak, lelaki itu sempat berjanji akan datang lagi secepatnya. Ia mengaku rumahnya tidak jauh dari pasar. Pasti kembali sesegera mungkin.
“Tunggu mi saja, Nek. Sebentar ji.” Lelaki tadi bergegas menjauh dari lapak.
“Iye’, tidak apa-apa ji.” Nenek Ina membalas ramah.
Lelaki itu menghilang di balik tenda dari terpal tua di ujung lorong pasar. Sementara Nenek Ina duduk menanti. Mengelap meja kecil di depannya sembari bermunajat semoga keringatnya hari itu berbuah lembaran-lembaran kertas yang bisa ia tukarkan di toko belakang pasar. Mungkin lima liter beras dan seikat plastik ikan kering cukup untuk beberapa hari ke depan, harapnya dalam hati.
Namun, hingga speaker musala pasar berdengung, dan muadzin mengumandangkan seruan yang agung, pertanda shalat Zuhur akan segera ditunaikan, tak tampak olehnya lelaki yang membungkus habis dagangannya tadi. Prasangkanya tetap sama, mungkin lelaki tadi ada urusan hingga harus menunda menemuinya. Diraihnya mukena usang dalam tas yang selalu dibawanya saat berjualan dan melangkah menuju musala. Saat kembali, situasi di lapaknya masih sama. Tak ada sesuatu yang menyiratkan kabar gembira.
Sinar Matahari kini mulai menghangat dan perlahan bola api raksasa itu meluncur pelan ke arah barat. Sementara para pedagang tampak mengemasi barang dagangannya dan satu persatu meninggalkan pasar. Sebagian lainnya duduk di depan toko menunggu jemputan mobil pickup untuk mengangkut belasan peti ikan yang tampak ringan tak berisi. Di sudut pasar, Nenek Ina masih menoleh kanan-kiri, harap-harap cemas menunggu lelaki pembeli pertama dan terakhirnya hari itu. Sampai pasar sepi, dan hanya tinggal sampah berupa-rupa yang terbang tertiup angin, ia masih berdiri di sana. Ingin ia menangis menyadari apa yang dialaminya. Tak ada seorangpun di sana selain dia. Ia tak ingin mengumpat dan mengeluh, apalagi berpikir lelaki tadi adalah seorang penipu. Sekali lagi, Nenek Ina menguatkan hatinya untuk tetap bersabar dan berharap. Kakinya mungkin akan tetap berpijak di sana sekiranya hujan tak datang tiba-tiba dan mengusirnya menjauh dari kompleks pasar. Sejak kecil, ia selalu yakin bahwa hujan adalah rahmat Allah. Seperti itu yang sering ia dengar dari leluhurnya dahulu. Tapi, dimana rahmat dalam hujan yang membasahi rambut -setengah beruban- nya petang itu? Kemana rintik-rintik air yang jatuh akan membawa harapannya untuk menenteng beberapa liter beras dan seikat plastik ikan kering ke gubuknya?
Sambil berlari kecil menuju jalan beton sempit yang biasa ia lewati saat pulang, Nenek Ina berdoa lirih dalam hati. Semoga Allah memberinya rahmat. Paling tidak suatu saat nanti ia akan mengerti makna rahmat yang tersirat di balik butir-butir hujan. Nenek Ina berlari agak cepat, tapi rahmat yang ia minta kembali secepat kilat di depan matanya. Tak pernah diduga sebelumnya, Allah begitu pengasih padanya, mengirim rahmat itu pada sebuah mobil Kijang Innova yang menghadangnya di jalan sempit itu. Kacanya terbuka dan tampak pembeli pertamanya pagi tadi tersenyum sambil meminta dengan sopan agar Nenek Ina bersedia naik agar tak semakin basah dihantam air hujan. Di dalam mobil, lelaki itu tak hentinya meminta maaf. Ada pekerjaan lain yang mengalihkan ingatan pada janjinya tadi. Ternyata ia adalah pemilik beberapa kafe dan warung kopi di Enrekang. Ia memesan kopi Nenek Ina dan memborongnya untuk dijadikan sample di warung kopi barunya di kecamatan Alla. Katanya, kopi Nenek Ina sangat khas. Sepulangnya di rumah, ia panik dan mencari Nenek Ina di lapak pasar, tapi tak dilihatnya. Bak gayung bersambut, di jalan sempit itulah ia dapat bernapas lega bisa menemukan Nenek Ina.
Terakhir, ia menawari Nenek Ina bekerja di warung barunya itu. Dengan wajah yang tampak lelah, perempuan tua itu hanya tersenyum. Wajahnya yang bercampur keringat, ditambah air hujan, mungkin juga oleh air mata bahagia, diusapnya dengan punggung tangan sambil tak henti-hentinya bersyukur dalam hati. Hari ini, ia menyadari, itulah arti rahmat dalam air hujan. Lewat seorang lelaki yang dengan teguh menepati janjinya. Dan, Nenek Ina makin yakin, Allah Sang Pemberi Rahmat, lebih-lebih tak pernah mengingkari janji-Nya.
Cerpen ini diikutkan dalam Lomba Cerpen yang diadakan oleh Dispustaka Enrekang.